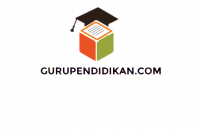Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai suku wana yang dimana dalam hal ini meliputi sejarah, bahasa, mata pencaharian, kekerabatan, agama dan kepercayaan, nah agar lebih memahami dan dimengerti simak ulasannya dibawah ini.
Sejarah Suku Wana
Berbicara tentang Suku Wana, pertama-tama yang harus diketahui adalah tentang sebuah kawasan yang terletak di pedalaman Propinsi Sulawesi Tengah bagian Timur. Kawasan yang dimaksud merujuk pada pemukiman Suku Wana yang meliputi wilayah pedalaman di Kabupaten Poso (terutama di Kecamatan Ampana Tete, Ulu Bongka, dan pedalaman Kecamatan Bungku Utara), Kabupaten Morowali (Kecamatan Mamolosato, Petasia, dan Soyojaya), dan wilayah pedalaman di Kabupaten Luwuk Banggai. (Sudaryanto, 2005).
Oleh masyarakat luar, Suku Wana sering disebut sebagai Tau Taa Wana yang artinya orang yang tinggal di kawasan hutan. Namun, suku wana sendiri lebih sering menyebut dirinya dengan Tau Taa (tanpa wana) atau orang Taa. Hal ini disesuaikan dengan bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Taa –selain karena dalam bahasa mereka tidak dikenal istilah wana (Camang, 2006).
Baca Juga : Sejarah Suku Tolaki
Dalam membangun kawasan pemukimannya, Suku Wana memilih untuk tidak membaur dengan penduduk mayoritas. Mereka memilih tinggal di kawasan pedalaman hutan Sulawesi Tengah dengan membangun semacam perkampungan yang disebut lipu. Dalam tradisi suku Wana, nama kelompok masyarakat yang menempati Lipu disesuaikan dengan nama kawasan di mana Lipu tersebut berada. Misalnya To Posangke, To Oewaju, To Kajupoli, To Bulang, To Kajumarangke, To Untunue, To Langada, dan sebagainya (Departemen Transmigrasi dan PPH RI, Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, 1999/2000).
Berdasarkan data sejarah, orang-orang Wana berasal dari sebuah kawasan di bagian selatan tenggara Pulau Sulawesi, tepatnya pada bagian Barat Daya atau Barat Laut Malili, di sebelah Tenggara Teluk Bone. Mereka sampai berada di pemukimannya saat ini diduga melalu gelombang migrasi pada ratusan tahun sebelum Masehi. Dari ciri-ciri fisik, kebudayaan material maupun dialek bahasa, Suku Wana termasuk dalam kelompok suku besar “Koro Toraja” yang rute migrasinya berawal dari muara antara Kalaena dan Maili kemudian menyusuri Sungai Kalaena dan terus ke utara melewati barisan Pegunungan Tokolekaju sampai akhirnya tiba di bagian tenggara pesisir Danau Poso (Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996/1997).
Dari tempat tersebut nenek moyang Suku Wana selanjutnya bergerak ke arah Timur Laut manyisir lereng Gunung Kadata menuju dataran Walati di Lembah Masewa yang dialiri Sungai La. Mereka terus bergerak ke arah Timur menyusuri lembah Sungai Kuse sampai akhirnya tiba di daerah Hulu Sungai Bau. Kemudian melanjutkan perjalanan migrasinya ke arah timur hingga mencapai Hulu Sungai Bongka (Kaju Marangka). Di sini mereka kemudian menetap dan berkembang menjadi kelompok etnik Tau Taa Waba (Mattulada, 1985).
Dari Kaju Marangka, menurut A.C Kryut, peneliti awal dari Belanda, dalam artikelnya yang berjudul De To Wana op Oost-Celebes (1930), sebagian imigran tersebut kemudian menyebar dan mengelompok menjadi empat suku yang memiliki dialek bahasa yang berbeda, yaitu :
- Suku Barangas, berasal dari Luwuk dan bermukim di kawasan Lijo, Parangisi, Wumanggabino, Uepakatau, dan Salubiro;
- Suku Kasiala, berasal dari Tojo Pantai Teluk Tomini dan kemudian bermukim di Manyoe, Sea, sebagian di Wumanggabino, Uepakatau, dan Salubiro;
- Suku Posangke, berasal dari Poso dan berdiam di kawasan Kajupoli, Toronggo, Opo, Uemasi, Lemo, dan Salubiro;
- Suku Untunue, mendiami Ue Waju, Kajumarangka, Salubiro, dan Rompi. Kelompok suku ini sampai sekarang masih menutup diri dari pengaruh luar (Yayasan Sahabat Morowali, 1998).
Pendapat sejarah di atas mendapat pembenaran dari para tetua adat Suku Wana, terutama tetua-tetua adat di Bulang dan tetua-tetua adat di Cagar Alam Morowali, yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah satu, berasal dari Tundantana, yaitu sebuah tempat di wilayah Kaju Marangka, yang berada dalam kawasan Cagar Alam (CA) Morowali. Tundantana diyakini sebagai tempat manusia pertama yang dititiskan dari langit dan kemudian melahirkan leluhur-leluhur Suku Wana.
Baca Juga : Sejarah Suku Pamona
Bahasa Suku Wana
Orang Wana menggunakan bahasa Wana, lazim disebut bahasa Ta’a yakni bahasa ingkar yang masih satu bagian dengan kelompok bahasa Pamona.
Mata Pencaharian Suku Wana
Walaupun masih dianggap masih hidup terasing secara kultural orang Wana sebenarnya tetap menjaga hubungan dengan penduduk pantai terutama untuk memproleh barang-barang dari besi. Untuk memperoleh barang-barang tersebut maka orang Wana berusaha mengumpulkan rotan, damar atau kayu besi untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan mereka dari pedagang dari pesisir.
Mata pencaharian mereka umumnya ialah berladang secara tebang, bakar dan berpindah jika kesuburan lahannya sudah hilang, tanaman ladang mereka ialah padi, jagung, ubi-ubian, labu, sayur-sayuran, kopi, pisang dan sedikit kelapa.
Selain meramu hasil hutan mereka juga berburu binatang liar, rusa, babirusa, monyet, burung maleo dan lainnya. Mereka berburu menggunakan senjata sumpitan beracun yang disebut sopu, tombak atau dengan perangkap.
Kekerabatan Suku Wana
Masyarakat terasing ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil dekat lahan perladangan mereka. Pemukiman dekat lahan ini terdiri dari 5-15 keluarga inti. Biasanya satu sama lain masih ada hubungan kekerabatan yang dekat.
Sebuah rumah tangga terdiri atas satu keluarga inti senior yang sering disertai oleh beberapa orang kerabat dekat sebagai kesatuan tenaga kerja, karena sebuah ladang dikerjakan oleh sekitar 5-10 tenaga kerja dewasa dan anak-anak yang sudah bisa membantu pekerjaan yang ringan.
Kepimpinan yang paling efektif dalam kehidupan sosial mereka ialah tokoh yang disebut Tautan Lipu, seorang lelaki senior yang berperan sebagai kepala pemukiman, sekaligus sebagai pemimpin tani dan syaman “dukun”.
Agama Dan Kepercayaan Suku Wana
Orang Wana telah sejak lama berhubungan dengan masyarakat pantai yang beragama Islam, seperti orang Bugis, Mori, Ampana, Bajau dan sebagainya. Karena itu sebagian dari mereka ada juga yang memeluk agama Islam. Ada pula yang kemudian memeluk agama Kristen Protestan yang dibawa oleg seorang penginjil di Lemo, namun yang masih tetap atau kembali kepada kepercayaan lama juga banyak.
Baca Juga : Sejarah Suku Baduy
Orang Wana yang masih memeluk kepercayaan lama mereka yang animisme dan dinamisme beranggapan bahwa agama mereka lebih tuas dari agama Kristen tetapi lebih muda dari agama Islam “karena agama Islam datang lebih dulu”, kepercayaan lama orang Wana berorientasi kepada adanya kekuatan-kekuatan gaib dan roh-roh yang mendiami tempat-tempat tertentu. Tempat yang mereka anggap sebagai daerah keramat dimana berdiam para roh ialah Gunung Tongku Tua “Tambosisi” yang tingginya sekitar 2.500 meter.
Pengaruh Sosial Suku Wana
Sebagaimana suku-suku pedalaman lainnya, Suku Wana juga menjalankan pola hidup yang secara simbolik terkait dengan upaya menjaga keharmonisan hubungan dengan para leluhur mereka. Satu hal yang paling menonjol dari upaya tersebut adalah dengan menjaga setiap jengkal tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam keyakinan Suku Wana, tanah (tana poga’a) diciptakan oleh Pue (Tuhan) adalah tidak lain untuk menjadi tempat hidup leluhur pertama mereka. Jadi, tanah tempat hidup mereka sekarang ini adalah tanah yang diberikan oleh Pue kepada nenek moyang mereka, yang selanjutnya diwarisi oleh Orang Wana saaat ini untuk dijaga kelestariannya. Jika tanah tersebut sampai rusak atau berubah fungsi, maka Pue dan leluhur mereka akan murka dan segera mendatangkan bencana alam seperti tanah longsor dan kebakaran hutan. Dalam kehidupan sehari-hari, Suku Wana menyebut tanah warisan leluhur mereka dengan “tana ntautua” atau tanah para leluhur (Yayasan Sahabat Morowali, 1998).
Keyakinan tentang kekeramatan tentang tana ntautua begitu melembaga dalam kehidupan Suku Wana hingga sekarang ini. Hal ini membuat Suku Wana selalu menolak setiapkali pemerintah berniat memindahkan (resettlement) mereka menuju kawasan pemukiman yang menurut pemerintah labih layak. Bagi Suku Wana, resettlement tersebut adalah sebuah pemaksaan untuk membuat mereka durhaka kepada leluhur, karena tidak lagi menjaga dan mempertahankan tana ntautua (Camang, Nunci, dan Tampobolan, 2005).
Keteguhan menjaga tana ntautua tersebut juga yang melahirkan implikasi-implikasi simbolik yang bagi Suku Wana telah menjadi semacam hukum adat yang harus dipenuhi. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
-
Menebang pohon berakibat pada petaka
Dalam keyakinan Suku Wana, pohon berfungsi sebagai perekat tanah leluhur. Jika pohon ditebang secara berlebihan, maka tanah enjadi tidak rekat lagi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Dengan demikian, dalam memaknai fungsi pohon, Suku Wana memiliki kesamaan dengan kaum konservasionis yang juga menganggap pohon berfungsi sebagai perekat tanah. Hanya saja keduanya memiliki alasan yang berbeda. Jika kesimpulan kaum konservasionis itu merujuk pada ilmu ekologi modern, maka kesimpulan Suku Wana merujuk pada cerita tentang kaju paramba’a. Tentu adat Suku Wana menjelaskan cerita kaju paramba’a sebagai berikut :
“kaju kele’i dan kaju paramba’a adalah kayu yang sengaja ditancapkan oleh Pue (Tuhan) tidak saja untuk melindungi leluhur Suku Wana tetapi juga untuk mengikat tanah leluhur atau tana ntautua agar kuat dan terus menyatu. Tapi karena kaju paramba’a kemudian ditebang oleh ngga, akibatnya timbul bencana tanah longsor, sehingga tana ntautua terpecah menjadi pulau-pulau. tana ntautua yang dulunya luas menjadi sempit. Setelah kaju paramba’a ditebang, maka yang sudah sempit akan menjadi semakin sempit.” (dalam Abubakar dan Camang, 2004).
Selain tanah dan kayu, satu komponen lagi yang menurut Suku Wana harus dilindungi adalah sungai. Pohon-pohon besar (kaju), tanah (tana), dan sungai (ue) adalah kesatuan yang saling terkait. Kesatuan itulah yang oleh Suku wana kemudian disebut sebagai hutan atau pangale. Jika salah satu unsur pangale tersebut dirusak, maka keseimbangan kesatuan tersebut akan rusak. Untuk itu, menurut keyakinan Suku Wana, jika manusia ingin kehidupannya di dunia ini terhindar dari bencana, maka mereka harus mampu menjaga kelestarian pangale nya (Yayasan Sahabat Morowali, 1998).
Baca Juga : Sejarah Suku Toraja
-
Pangale “Orang tua” yang harus dilindungi
Makna simbolik lain yang juga melembaga sampai saat ini di kalangan Suku Wana sebagai hasil dari penafsiran terhadap cerita kajuparamba’a adalah “hutan sebagai orang tua”. Hal ini pernah disampaikan oleh Jeo, pemula adat dari Lipu Mpoa, dalam acara “Lokakarya dan Dialog Nasional Promosi Sistem Hutan Kerakyatan,” di Jakarta tanggal 3 – 7 Juli 2010. Ketika itu, Jeo yang biasa dipanggil Apa Inse, memaparkan :
“Istilah hutan bagi kami adalah Pangale. Dia adalah ibu bagi masyarakat kami. Kenapa hutan itu kami jaga karena hutan (pangale) adalah ibu kami. Dalam melakukan kapongo (membuka hutan), kami bikin upacara adat, karena itu termasuk memindahkan nyawa ibu. Navu (kebun) kami akan hidup karena dalam lindungan ibu (pangale)… kami marah pada HPH karena merusak hutan. Kami yang pelihara hutan justeru dianggap merusak” (dalam Camang, Nunci, dan Tampubolon, 2005).
-
Pangale : Tempat Keramat
Selain memaknai hutan berdasarkan penafsirannya terhadap cerita kaju paramba’a, komunitas Suku Wana juga memiliki pemahaman tentang hutan berdasarkan keyakinannya terhadap pandangan dunianya (kosmologi). Dari pandangan dunia ini, mereka kemudian menafsirkan hutan (pangale) sebagai tempat sakral (keramat) yang mesti diperlakukan secara religio magis. Suku Wana percaya bahwa terdapat tiga jenis kekuatan roh yang menjaga hutan, yaitu roh-roh suci (malindu maya, malindu oyo, lamba jadi) roh-roh jahat (walla), dan arwah-arwah manusia (rate). Menyebut nama roh-roh ini adalah pantangan bagi Suku Wana ketika mereka berada di dalam hutan, kecuali sedang meakukan ritual-ritual tertentu (Camang, Nunci, dan Tampubolon, 2005). Keyakinan akan adanya roh penunggu hutan tersebut membuat Suku Wana memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelestarian kawasan hutan. Sebab, jika hutan dirusak, roh-roh penunggu hutan akan marah, dan selanjutnya akan mendatangkan malapetaka kepada manusia yang merusak hutan tersebut.